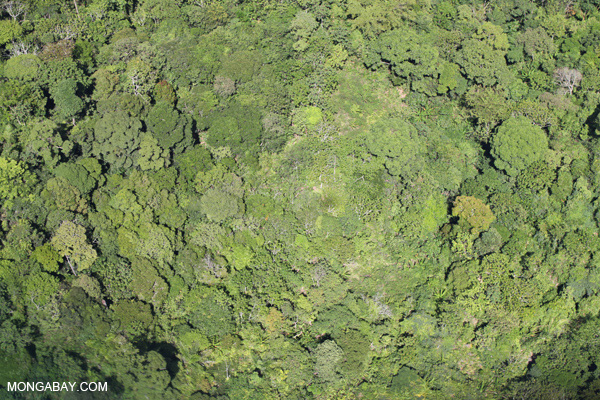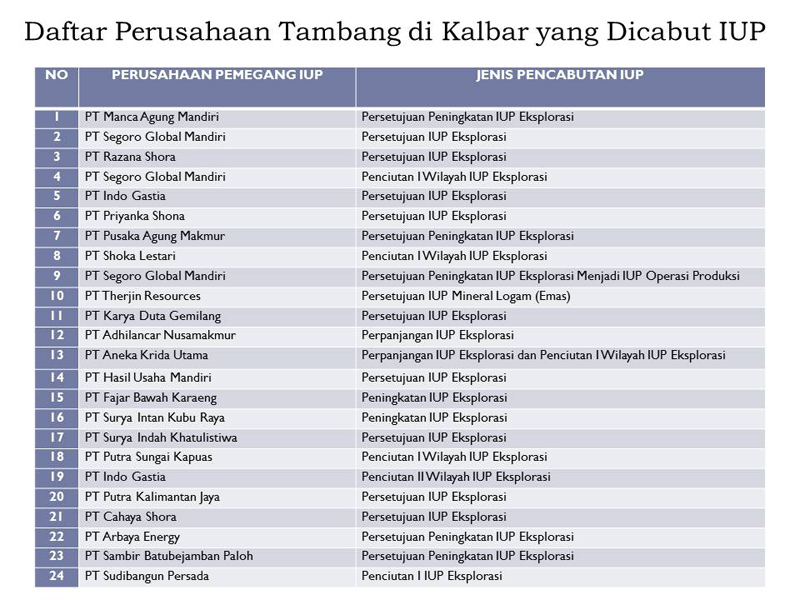Persoalan mendasar kehidupan masyarakat di wilayah pesisir adalah minimnya air bersih dan tanpa adanya penerangan. Foto: Rhett Butler
“Listrik? Itulah mimpi kami selama ini. Beberapa tahun lalu, ada kabar dusun kami akan dialiri listrik, tapi sampai sekarang belum ada,” kata Bandarsyah, ketua RT Dusun Rengas Merah, Desa Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis (19/02/2015).
Guna memenuhi kebutuhan penerangan, Bandarsyah dan keluarga lainnya di dusun itu terpaksa menggunakan mesin genset yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). “Yang tidak mampu membeli mesin genset ya terpaksa menggunakan lampu minyak tanah,” katanya.
Itu dusun yang jauh dari garis pantai. Bagaimana dusun atau desa yang berada di garis pantai? “Listrik mengalir di dusun kami? Mungkin lebih baik bercita-cita menunaikan ibadah haji, jauh lebih mudah. Mengumpulkan dana, menjaga kesehatan, dan berdoa. Kalau soal listrik, berdoa dengan Tuhan pun rasanya pemerintah belum tergerak mengalirkan listrik ke desa kami,” kata Karnawi, Kepala Desa Simpang Tiga Makmur, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.
Sama seperti di Dusun Rengas Merah, masyarakat di Desa Simpang Tiga Makmur juga menggunakan genset atau minyak lampu untuk penerangan atau menyalakan alat elektronik lainnya.
Bedanya, kehidupan masyarakat di Desa Simpang Tiga Makmur, sedikit lebih baik dibandingkan dengan warga Dusun Rengas Merah. Di desa tersebut sumber pencarian selain menangkap ikan, memelihara udang, juga membuat terasi yang cukup terkenal di Indonesia. Hampir semua rumah di desa tersebut memiliki genset, sehingga penggunaan alat elektronik pun dapat dilakukan.
Sedangkan di Dusun Rengas Merah, kehidupan hanya mengandalkan hasil pertanian, seperti padi dan sayuran. “Biaya hidup kami di sini cukup besar untuk penerangan, dibandingkan makan dan kebutuhan lainnya,” kata Bandarsyah.
Selain listrik, persoalan yang cukup penting bagi masyarakat di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan yakni air bersih. Guna mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi, mereka terpaksa membeli air mineral. Air dari sungai dan rawa, hanya dapat digunakan untuk mandi dan mencuci.

Desa Simpang Tiga Makmur, Kecamatan Tulung Selapan, OKI, Sumsel, ini sejak Indonesia merdeka belum pernah dialiri listrik. Foto: Taufik Wijaya
Pusat tenaga surya
Persoalan yang dialami masyarakat pesisir timur tersebut, sudah diketahui Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel). Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Sumsel tidak akan membuat instalasi listrik yang menggunakan bahan baku mineral, melainkan tenaga sinar matahari.
“Rencananya akan dibangun pusat tenaga listrik sinar matahari yang berada di atas lahan seluas 20 ribu hektar. Tiang-tiang penangkap sinar surya itu akan tersebar,” terang Gubernur Sumsel Alex Noerdin, seperti yang diucapkan M. Ali Akbar, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Infrastruktur, saat mengunjungi Dusun Rengas Merah, Desa Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Kamis (19/02/2015).
Pemasangan tiang penangkap sinar matahari ini bukan menggusur lahan warga atau hutan. “Bisa saja tiang itu berada di tengah sawah, tepi pantai, atau sekitar rumah penduduk. Yang jelas, dekat permukiman warga yang membutuhkan aliran listrik. Luasan 20 ribu hektar tersebut, merupakan wilayah pemukiman,” katanya.
Rencana pembangunan tengah disusun, “Sebab sudah ada investor yang akan melaksanakan proyek tersebut,” kata Ali.

Rumah di tengah lahan gambut di Tulung Selapan, OKI, Sumsel, ini tidak pernah disentuh listrik. Foto: Taufik Wijaya
Terhadap rencana tersebut, Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Lingkungan Hidup, menilainya cukup baik. “Itu cukup baik, sebab tidak menggunakan energi fosil yang menyebabkan peningkatan pemanasan global,” katanya.
Selain tenaga sinar matahari, energi alternatif yang akan dikembangkan di wilayah pesisir ini adalah bio diesel yang berasal dari tanaman nyamplung. “Solar yang dihasilkan lebih diperuntukan bagi kendaraan, seperti perahu nelayan atau kapal angkutan,” katanya.
Tapi yang lebih penting, pengembangan tersebut juga bersamaan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan hidup. “Semua pihak, khususnya pemerintah dan pelaku usaha, harus segera memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan produksi pertanian, dan perikanan,” ujarnya.
Ditambahkan Ali, guna mencapai hal tersebut, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. “Untuk transportasi tampaknya melalui perbaikan angkutan air dan penerbangan. Angkutan darat tetap dibutuhkan, tapi jangan diutamakan, sebab akan banyak membutuhkan lahan, sehingga hutan dan lahan gambut akan terganggu. Jika transportasi air dan udara diandalkan, sungai dan rawa bukan ditimbun justru dijaga,” ujarnya.
Penerbangan tersebut dapat menggunakan bandara di atas lahan kering atau sungai. “Di sini kan banyak sungai yang lebar dan dalam yang dapat digunakan pendaratan pesawat terbang kecil,” kata Ali.
“Ya, rencana ini akan terwujud bukan dalam waktu secepatnya, mungkin butuh waktu 5-10 tahun. Bertahap. Tapi kita harus memikirkannya sejak dini, sehingga saat dilakukan tidak berdampak pada lingkungan, dan memang mendorong kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumsel yakin wilayah pesisir timur ini akan kembali berjaya seperti masa Kerajaan Sriwijaya. Bedanya, saat ini selain menjadi sentra pangan dan industri kehutanan, juga pariwisata yang berbasis lingkungan hidup,” ujarnya.

Rata-rata masyarakat yang hidup di pesisir timur Sumatera Selatan belum pernah bersentuhan listrik. Foto: Taufik Wijaya
Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio
Nasib Desa di Pesisir Timur Sumatera Selatan: Tanpa Listrik dan Minim Air Bersih was first posted on February 21, 2015 at 1:11 am.